Pada suatu sore di ruang kerjanya di LAF, Dina Danish,
seniman Mesir yang sedang residensi dalam rangka Biennale Jogja XII, duduk dan
berbicara dengan tiga orang dalam tiga bahasa yang berbeda: ia mengobrol dengan
saya, asistennya, dalam bahasa Inggris; membalas sapaan Magdi Mostafa, seniman Mesir
yang berbagi ruang residensi dengannya, dalam bahasa Arab; dan mendiskusikan
sesuatu dengan tunangannya Jean-Baptiste Maitre dalam bahasa Perancis.
Dina Danish memang sangat internasional. “Saya menguasai 3,5
bahasa,”katanya, “Inggris, Jerman, dan Arab. Perancis yang setengahnya. Well,
kalau kita anggap Arab Mesir dan Arab Klasik dua bahasa yang berbeda berarti
saya bisa 4,5 bahasa.”katanya sambil tertawa.
Perempuan 32 tahun ini berkebangsaan Mesir, lahir di Paris, tinggal
di Amsterdam, akan menikah dengan orang Perancis, dan mengenyam pendidikan
Amerika serta Jerman. Minatnya terhadap bahasa terbentuk sejak SMA di mana ia
belajar di sekolah berkurikulum Jerman di Mesir. “Di sekolah itu saya harus
belajar dengan bahasa Jerman seakan-akan itu bahasa ibu saya.”kenangnya.
Bagaimana manusia mempelajari dan menyikapi bahasa yang lain dari bahasa ibunya
sendiri adalah sesuatu yang menarik untuk Dina Danish. “Bahasa adalah sarana
komunikasi yang paling penting bagi manusia. Selain itu saya juga senang
menulis.”tuturnya. Dina sekarang sedang menggarap sebuah buku tentang lelucon
dari seluruh dunia.
Perjalanannya ke berbagai tempat di dunia juga membawanya
mengumpulkan berbagai produk bahasa dari kebudayaan-kebudayaan yang berbeda. Lelucon,
takhayul, salah tafsir, pokoknya segalanya yang berhubungan dengan permainan kata-kata
dan cerita menggugah rasa ingin tahunya. Semua itu kerap kali ia dekonstruksi
dalam berbagai bentuk karya seni, entah itu lukisan, video, penampilan,fotografi,
atau instalasi. Bentuk seninya terkadang
bisa jadi sangat lucu tapi membingungkan. Menurut Buku Panduan Biennale XII, ciri
khas Dina Danish adalah memadukan seni konseptual dengan bahasa. Ia tidak
membatasi jenis medianya untuk berkarya.
“Saya selalu senang mempelajari media-media yang baru. Saya
tidak pernah merasa satu media lebih penting dari yang lain,”katanya. “Gisa,
keahlianmu adalah bahasa bukan? Untuk jadi ahli bahasa kamu harus terus belajar
kosa kata baru. Nah bagi saya media seni adalah kosa kata, yang jumlahnya ada
banyak dan harus terus saya pelajari.”jelasnya. Memang, saya menyadari bahwa
saya tidak bisa menjawab ketika beberapa teman saya bertanya Dina itu seniman
apa. “Lukisan? Foto? Video?”tanya mereka. Saya harus menjawab dia melakukan
semuanya.
Walau demikian, Dina memulai berkesenian dengan mempelajari
lukisan di The American University in Cairo. Ia mendapatkan gelar S2 di San
Francisco dalam bidang lukisan dan drawing. “Tapi selama kuliah S2 saya jarang
sekali melukis,”katanya. “Everyone who
made any painting is usually problematic.”ujarnya sambil tertawa.
Menurutnya lulus kuliah seni dengan karya lukis itu sangat susah. “Saya membuat
segalanya kecuali lukisan untuk lulus kuliah,”katanya.
Maka, daripada membatasi diri pada media berkesenian, Dina
Danish memilih mencirikan diri pada sebuah metode kerja yang unik. “Saya selalu
mulai dari sesuatu yang sangat sederhana. Saking sederhananya mungkin orang
akan mengira itu suatu kekonyolan, kebodohan, atau kebanalan. Saya memberi
perhatian pada sesuatu yang sangat sederhana, lalu mengeksplorasinya sejauh
mungkin.”
Salah satu yang
menjadi minat besarnya adalah tongue
twisters, rangkaian kata-kata yang harus diucapkan dengan cepat sampai kita
keseleo lidah. Pada hari-hari pertama ia bekerja di Jogja, saya memasang status
di laman Facebook saya bahwa kami sedang mengumpulkan tongue twisters dari Indonesia. Responsnya luar biasa. Teman-teman
mengirimkan tongue twisters yang
mereka tahu dari bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Dari yang biasa saja sampai
yang sulit, dari yang lucu sampai yang saru. Dina terutama tertarik pada “Kuku
kaki kakek kaku-kaku”, “Satu tongkol, dua tongkol, tiga tongkol… sepuluh tongkol”,
“Satu sate tujuh tusuk”, dan “Laler lare rolas”
“Kita bisa membuat banyak hal dari sini,”jelasnya dengan
bersemangat siang itu di LAF. “Misalnya ‘tongkol’ ini. Kita bisa membuat sebuah
lukisan ikan tongkol, satu di baris paling atas, dua di baris bawahnya, tiga di
baris bawahnya lagi, sampai sepuluh tongkol di baris paling akhir.”
“Kuku kaki kakek kaku-kaku” terpatri dalam pikirannya karena
bunyinya yang lucu, sedangkan bayangan visual “Satu sate tujuh tusuk,”
menurutnya sangat menggelitik. Setelah mengumpulkan materi dan memikirkannya,
Dina memutuskan akan membuat sebuah karya video dari “Satu sate tujuh tusuk”
dan “Laler lare rolas”. Dalam video itu, sebuah kelompok koor akan menyanyikan “Sweet
Child of Mine” yang liriknya diganti seluruhnya dengan “Satu sate tujuh tusuk”
dan “I Dreamed a Dream” yang liriknya diganti dengan “Laler lare rolas”.
Sebagai native speaker, saya disuruh
mencoba menyanyikan gubahan kami itu. Saya benar-benar merasa konyol dan bodoh,
terutama saat menyanyikan nada-nada sedih “I Dreamed a Dream” dengan “laler
lare rolas”, namun Dina dan Jean-Baptiste memandang saya menyanyi dengan mata
berbinar-binar seperti melihat gunung emas.
“Perfect,”katanya.
“Kedua lagu tersebut sama-sama lagu yang familiar bagi orang-orang di seluruh
dunia, maka ketika kamu menyanyikannya dengan lirik dari bahasa lain,
keanehannya sangat terasa.”
Sayangnya proyek tongue
twisters ini harus dibatalkan. Waktunya terlalu sempit dan biayanya mahal,
sementara kami harus menyewa dan melatih sekelompok koor, mencari partitur dua
lagu dan menggubah liriknya, menyewa studio untuk rekaman, menyewa tim film-maker, memproduksi setting, dan
macam-macam lagi. “Tidak masalah. Kami tetap bisa menggunakan tongue twisters ini untuk hal-hal lain.”kata
Dina. Sebagai gantinya, ia memamerkan video “The Sailor’s Shirt” yang ia buat
di Amsterdam pada tahun 2011.
 |
| "The Sailor's Shirt" di Lantai 3 JNM, Biennale Jogja XII |
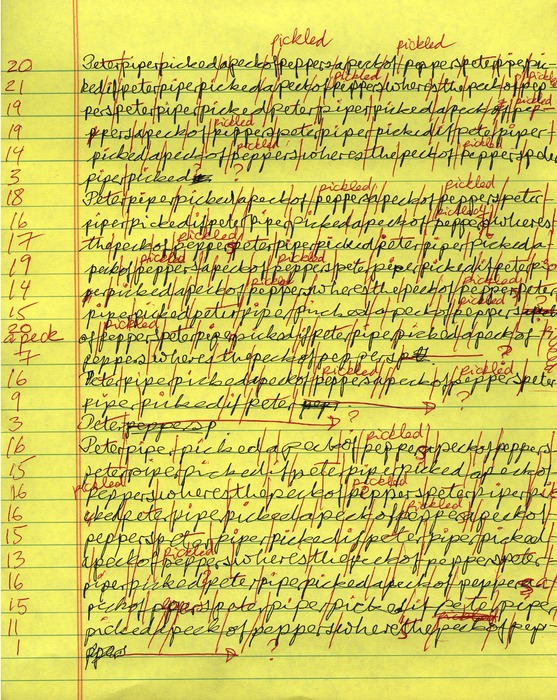 |
| Salah satu respons Dina terhadap tongue twisters. Bukannya mengucapkannya dengan cepat, Dina menuliskannya dengan cepat, lalu mengkoreksinya dengan warna yang berbeda. |
Walau demikian, ide tongue
twisters ini sangat unik dan menarik. Tongue
twisters memenuhi kriteria “sederhana”, “konyol”, dan “banal”. Menurut
Dina, kalimat-kalimat tongue twisters di
seluruh dunia tidak memiliki konten yang penting. Arti dari kalimat “kuku kaki kakek
kaku-kaku” memang sangat banal, tidak penting, dan bahkan konyol. Ketika ia
meminta saya menerjemahkannya, saya bilang, “Grandfather’s toe nails are stiff.”
yang tentu saja tidak jelas, tidak penting, konyol, dan bodoh.
Menurut Dina, yang penting dari tongue twisters adalah trik pengucapan dan bunyi kata-katanya. Buat
saya, “kuku kaki kakek kaku-kaku” konyol karena saya paham artinya, tapi untuk
Dina, bunyinya sangat menarik. “Kukukakikaku…
you know, just the sound of things. Nothing at all.” ujarnya. Bunyi bahasa
yang menarik itu yang membuat tongue
twisters susah diucapkan. Tongue twisters
diciptakan supaya kita salah berucap. “They
are meant to be failed at. Dalam bahasa apa pun. Mau itu bahasa ibumu, mau
itu bahasa asing yang sudah sangat kamu kuasai, kamu akan selalu gagal
mengucapkan tongue twisters. Seperti ‘laler
lare rolas’. Kalimat ini sama susahnya buat kita berdua.”ujarnya. “The sound is bound to failure. The content
is meaningless.” cukup banal dan konyol bukan?
“Jadi menurut saya, okay, kita memang ditakdirkan untuk
gagal mengucapkan tongue twisters. Kenapa
susah payah melakukannya?” tuturnya. Maka Dina Danish berupaya mencari alternatif
pengganti pengucapan oral yang selalu gagal itu, supaya kita bisa berhasil
dengan tongue twisters.
Dina menunjukkan salah satu video performance yang ia buat berdasarkan tongue twisters dalam bahasa Inggris “Yellow butter, purple jelly, red jam, black bread. Spread it thick, say
it quick”. Dalam performance itu
ada tiga atau empat aktor yang duduk di depan meja, mengolesi roti hitam dengan
mentega, selai blueberry, dan selai strawberry, lalu memakannya dengan cepat.
Aksi itu diulangi beberapa kali dengan tempo yang makin lama makin cepat. Lalu
setelah selesai mereka langsung meninggalkan meja.
“Give the meaninglessness a form.” Katanya ketika menguraikan inti
dari proyeknya. Memberi bentuk kepada ketiadaan arti, entah dalam bentuk performance, lukisan, patung, nyanyian,
dan lain sebagainya. Dengan memberi bentuk yang berarti pada kebanalan makna,
Dina Danish merasa telah mengatasi kegagalan pengucapan oral. Selain itu,
terciptalah suatu karya seni yang bisa berdiri sendiri pula.
Pengucapan oral dan bunyi suatu bahasa adalah salah satu unsur
bahasa yang menarik bagi Dina Danish. “Sebelum kamu menguasai suatu bahasa, kamu
harus membiasakan dirimu dengan bunyi dari bahasa tersebut.”ucapnya. Ia
mengambil contoh seorang anak kecil yang baru belajar berbicara. Anak kecil
tersebut akan memulai belajar bahasa dengan mendengarkan dan meniru suara.
Setelah itu baru ia menggunakan bentuk-bentuk suara itu untuk menyampaikan
makna, misalnya minta makan atau minum. “Yang menarik dari bunyi bahasa adalah
cara pengucapannya. Pronunciation. Bagaimana
kamu menggerakkan mulut dan lidahmu untuk mengucapkan kata-kata itu dengan benar.
Pronunciation bisa menjadi sangat
menarik ketika kamu sedang mempelajari bahasa baru. Ketika kamu benar-benar
bisa menguasai bahasa tersebut, kamu bisa berbicara menggunakan bahasa tersebut
tanpa aksen. Itu benar-benar sulit.”katanya.
Masih terkait dengan bahasa, Dina Danish juga tertarik
dengan bentuk tulisan dari kata-kata tersebut. “Bagaimana jika bentuk-bentuk
huruf itu tidak bermakna? Hanya garis-garis dan bentuk, bukan? Hanya
bentuk-bentuk yang saling terkait satu sama lain.” Katanya. Selain itu Dina
juga tertarik dengan ragam bentuk wadah bahasa. Maka ia punya kebiasaan
mengumpulkan kertas dari tempat-tempat residensinya di seluruh dunia. Kertas bergaris
adalah bentuk wadah kosong yang menunggu untuk diisi produk bahasa. Karya
batiknya, Lined Paper, yang dipajang di LAF pun juga merespon bentuk kertas
dari buku-buku tulis yang ia beli di Jogja.
Walau sangat tertarik dengan bahasa, Dina tidak belajar linguistik
secara khusus. Ia mengambil kuliah wajib linguistik selama kuliah master, senang
membaca dan menghadiri seminar tentang linguistik, namun tidak pernah
mendalaminya. Karya seninya yang merespon bahasa lebih berakar pada pengalaman
personal ketika ia terekspos suatu bahasa asing atau produk bahasa yang tidak
biasa. Reaksi personalnya membuatnya lebih mudah dalam mendekonstruksi teks
menjadi bentuk visual. “Bentuk teks dan visual saling mendukung. Tidak ada yang
lebih penting dari yang lain.”tuturnya.
Bagaimana dengan tanggapan audiens karya seninya? Ketika
mereka melihat hal-hal yang lumrah dan bahkan cenderung konyol dari kehidupan
sehari-hari didekonstruksi dalam bentuk karya seni? “Kebanyakan tertawa,”kata
Dina. Video-video performance-nya
ganjil tapi menggelitik. Menurutnya, memang bentuk karya seninya berhubungan
dengan bagaimana membuat orang tertawa.
Bekerja dengan Dina Danish selama enam minggu merupakan
pengalaman baru yang sangat berharga bagi saya. Saya, yang sama sekali bukan
anak seni, jadi tahu bahwa seniman tidak hanya bisa mengkhususkan diri pada
suatu media, namun bisa juga mengkhususkan diri pada konsep dan metode
berkarya. Dina memberi perhatian khusus pada hal-hal konyol dan bodoh yang kita
lakukan sehari-hari lalu mengeksplorasinya sejauh mungkin. Hal-hal tersebut ia
ubah menjadi berbagai bentuk karya seni yang bisa membuat orang mengerutkan
kening karena kebingungan atau mendengus tertawa karena kekonyolan yang ia tonjolkan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar